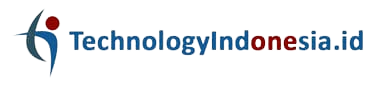Jakarta, Technology-Indonesia.com – Permasalahan pertanian tidak hanya sebatas pemenuhan pangan dan peningkatan produksi. Tantangan ke depan akan semakin kompleks sebagai akibat dampak perubahan iklim seperti terjadinya kenaikan muka air laut. Pada beberapa daerah di pesisir pantai menyebabkan cekaman lingkungan berupa peningkatan salinitas dan penurunan luasan lahan sawah.
Peneliti Balai Penelitian Lingkungan Pertanian (Balingtan) Rina Kartikawati mengatakan bahwa salinitas pada lahan pertanian akibat naiknya muka air laut tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Beberapa negara yang sentra pertanian berada di pesisir atau delta sungai besar juga terancam dengan naiknya permukaan air laut.
“Daerah pesisir pantai merupakan daerah paling rawan karena meningkatnya air laut atau rob dan intrusi yang mengakibatkat kadar garam dalam tanah dan air meningkat. Pada beberapa sentra produksi padi berada di pesisir utara Pulau Jawa seperti Serang, Cilacap, Indramayu, Kendal, dan Demak kenaikan muka air laut dikhawatirkan menimbulkan dampak terhadap produktivitas pertanian,” kata Rina saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis Online Balingtan dalam rangka perayaan Hari Tanah Sedunia pada Kamis (2/12/2021).
Selain karena naiknya permukaan air laut, salinitas di lahan pertanian juga dapat disebabkan oleh input limbah industri, evaporasi lebih tinggi dari presipitasi, bahan induk tanah mengandung mineral garam, dan persaingan pemakaian dengan usaha lain seperti tambak.
Pada kondisi cekaman salinitas, proses pertama yang terjadi adalah terganggunya keseimbangan air dan hara. “Pada kondisi salinitas hampir semua tanaman tidak dapat tumbuh dan berkembang secara normal sehingga berpengaruh pada produktivitasnya, kecuali tanaman-tanaman yang memiliki toleransi tinggi terhadap kondisi salinitas,” terang Rina
Peningkatan hasil dan keberlanjutan budidaya di lahan berkadar garam tinggi memerlukan suatu sistem yang terintegrasi dengan melibatkan penggunaan varietas toleran salinitas tinggi dan pengelolaan nutrisi bagi tanaman yang efektif. Pengelolaan lahan salin bisa dilakukan dengan pengelolaan air, penggunaan bahan amelioran, penggunaan varietas toleran salinitas, dan pemanfaatan mikroorganisme.
Lebih lanjut Rina menerangkan bahwa pengelolaan air merupakan salah satu kunci dalam mengatasi salinitas di lahan pertanian wilayah pesisir pantai. Infrastruktur dan pengelolaan air yang kurang tepat dapat memperparah intrusi dan rob pada lahan pertanian.
“Pada areal persawahan di pesisir pantai yang tidak mempunyai infrastruktur irigasi memadai, masuknya air asin sulit dihindari sehingga pada akhirnya lahan pertanian berubah menjadi tambak udang atau ikan,” kata Rina.
Bagi petani yang tidak mempunyai banyak modal, sawah yang terdampak air asin dibiarkan saja karena untuk mengubahnya menjadi tambak membutuhan biaya yang cukup tinggi. Selain itu, pembuatan tambak membutuhkan akses yang baik untuk peralatan berat.
Di beberapa daerah dengan infrastruktur pengairan cukup memadai. Petani dapat menanam padi pada musim penghujan dengan suplai air tawar dari saluran irigasi yang terhubung dengan sungai air tawar. Namun pada musim kemarau, petani tidak dapat menanam padi karena air tawar tidak cukup tersedia di saluran irigasi. “Selain itu, petani tidak dapat menanam palawija karena kadar garam tanah cukup tinggi bagi tanaman palawija yang menyebabkan tanaman mati,” imbuhnya.
Pada beberapa wilayah pesisir, meskipun lahan pertaniannya berbatasan dengan pantai namun dampak intrusi tidak secara nyata mempengaruhi pertumbuhan tanaman dan hasilnya. Hal ini disebabkan adanya sistem pengaturan air yang baik.
Rina mengungkapkan studi yang dilakukan di wilayah pesisir pantai di Bangladesh, jika air dari sungai dapat masuk dan disimpan pada kanal-kanal yang ada dalam areal persawahan, ketersediaan air tawar akan cukup mengairi sawah sebelum air tersebut terkontaminasi dengan air asin. “Penataan kanal-kanal yang ada di areal persawahan dipersiapkan untuk mengatasi masuknya air asin dari saluran utama,” tuturnya.
Peningkatan produktivitas tanaman pada lahan salin juga dapat dilakukan melalui pemberian amelioran. Bahan organik seperti kompos, pupuk kandang dapat digunakan untuk meningkatkan sifat fisik, kimia dan biologi tanah yang terdampak salinitas. Remediasi lahan sawah terdampak salinitas dapat dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan kimia seperti gypsum, kalsit, kalsium klorida serta bahan organik seperti pupuk kandang, kompos, dan bahan pembenah alami lainnya.
Penggunaan varietas unggul toleran salinitas juga dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Varietas padi tahan salinitas yang telah dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) antara lain Inpara 3, Inpara 4, Inpara 5, Inpara 8, Inpara 30, Inpari 34, dan Inpari 35.
“Beberapa varietas toleran salinitas seperti Batanghari, Banyuasin, dan Inpara 5 memiliki emisi metan yang cukup rendah. Ini bisa menjadi salah satu upaya kita untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari lahan salin,” kata Rina.
Pengelolaan lahan salin juga bisa dilakukan melalui bio-remediasi menggunakan mikroba. Bio-remediasi merupakan salah satu inovasi dalam penanggulangan permasalahan lingkungan yang ramah terhadap lingkungan, tahan pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan, dan menghasilkan berbagai senyawa metabolik sekunder.
Rina mencontohkan, spesies genus Streptomyces mempunyai potensi sebagai bio-remediasi untuk tanah-tanah salin. Arthrobacter woluwensis, Microbacterium oxydans, Arthrobacter aurescens, Basillus megaterium, dan Bacillus aryabhattai merupakan isolat bakteri yang toleran pada kondisi salinitas.
Menurut Rina, pengelolaan komponen teknologi pada lahan terdampak salinitas harus dilakukan secara terintegrasi dalam upaya menurunkan tingkat salinitas lahan pertanian. “Penyelesaian permasalahan salinitas di wilayah pesisir melibatkan banyak pihak yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur irigasi, budidaya pertanian, dan petani atau kelompok tani,” pungkasnya.
Pengelolaan Air dan Varietas Unggul Kunci Atasi Salinitas Lahan di Pesisir Pantai